
LIPUTAN KHUSUS:
RUU Konservasi Belum Akui Peran Penting Masyarakat Adat
Penulis : Gilang Helindro
Masyarakat adat yang terbukti mempertahankan keanekaragaman hayati, menjaga pohon dan hewan.
Konservasi
Senin, 10 Juni 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Kebijakan dan perencanaan keanekaragaman hayati di Indonesia semestinya didorong melalui RUU Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem ( RUU KSDAHE) yang masih dalam proses legislasi di parlemen, serta dokumen IBSAP (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan) yang saat ini masih dalam proses penyusunan dan kesepakatan di tingkat Kementerian dan Lembaga. Namun, menurut Working Group ICCas Indonesia (WGII), yang mencermati proses penyusunan RUU KSDAHE maupun IBSAP, secara substansi, draft RUU KSDAHE versi terakhir secara muatan lebih buruk daripada draft awal yang diusulkan DPR RI.
IBSAP adalah implementing policy yang akan meneruskan komitmen pemerintah pada Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF) untuk mencegah dan mengatasi krisis keanekaragaman hayati hingga tahun 2030.
Menyikapi draft tersebut, organisasi masyarakat sipil pada 19 Januari 2024 telah menyampaikan sikap penolakan terhadap RUU KSDAHE mengingat banyaknya substansi yang berpeluang memperbesar potensi krisis dan konflik keanekaragaman hayati dan hak asasi manusia. Ormas juga mengkritik penyusunan draft tersebut yang elum secara maksimal mengikutsertakan masyarakat adat, komunitas lokal, dan publik sebagai aktor penting dalam konsultasi dan penyusunan kebijakan.
Kasmita Widodo, Koordinator WGII, dalam keterangan resminya menyampaikan UU nomor 5 tahun 1990 telah menorehkan sejarah kelam dari praktik penetapan kawasan konservasi yang telah dilakukan dengan proses yang ugal-ugalan dan abai terhadap proses FPIC. Salah satu konflik laten itu terjadi di Ruteng pada tahun 2004, akibat tumpang tindih wilayah adat dengan Taman Wisata Alam Ruteng, yang menyebabkan 6 orang meninggal, 28 orang luka luka, dan 3 orang cacat seumur hidup.

Baru-baru ini, kata Kasmita, konflik lama ini terulang dengan ditangkapnya Pemangku Adat (Tua Teno) Ngkiong Mikael Ane di Desa Ngkiong Dora. Ia dipenjarakan karena dianggap menduduki wilayah Taman Wisata Alam Ruteng. Padahal Mikael Ane dan leluhurnya telah berdiam dan berkegiatan di wilayah hutan tersebut sebelum Taman Wisata Alam Ruteng ada.
“Kasus ini satu dari sebagian besar kasus konflik dalam penetapan kawasan konservasi yang terjadi di seluruh Nusantara,” kata Kasmita, dikutip Rabu, 5 Juni 2024.
RUU KSDAHE maupun IBSAP harusnya dapat menjadi harapan untuk memperbaiki krisis keanekaragaman hayati, iklim, maupun konflik dalam penyelenggaraan konservasi. Kebijakan-kebijakan ini seharusnya dapat mengakui kontribusi masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini telah melindungi keanekaragaman hayati melalui kearifan lokalnya, sebagaimana yang didorong pada komitmen KM-GBF.
Pada 1 Juni 2024, WGII merilis data terbaru dengan mencatat angka registrasi Areal Konservasi Kelola Masyarakat Adat (AKKM) pada sistem registrasi AKKM di WGII. Saat ini telah mencapai angka 524.501 juta hektare dengan potensi AKKM mencapai 4,2 juta hektare. Data ini hanya sedikit dari praktik baik dan efektif yang dilakukan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Jika dibandingkan data wilayah adat yang diregistrasi di BRWA yang saat ini telah mencapai hampir 28 juta hektar,e kata dia, tentu potensi AKKM bisa jauh lebih besar.
Dolvina Damus mewakili Masyarakat Adat Dayak Lundayeh mengatakan, praktik konservasi yang mereka lakukan beribu-ribu tahun seperti misalnya sistem perlindungan di Tana Ulen belum diakui dalam RUU KSDAHE. Di sisi lain, RUU ini berpotensi untuk memperburuk situasi di kampung dan memicu konflik baru dengan Masyarakat Adat.
“Kami berharap pemerintah tidak tergesa-gesa untuk mengesahkan RUU KSDAHE jika memang belum sesuai dengan usulan kami. Apalagi kalau sampai ada sanksi pelepasan hak atas tanah di Areal Preservasi, ini adalah masalah besar,” ungkap Dolvina.
Cindy Julianty, Program Manager WGII menambahkan hasil analisis bersama antara BRWA, WGII, dan FWI menunjukkan bahwa 72 persen ekosistem esensial seperti mangrove, karst, area koridor satwa HCV dan key biodiversity areas berada di wilayah adat. Study FWI menunjukan bahwa 70 persen tutupan lahan di wilayah adat masih dalam kondisi baik, namun dalam kondisi demikian, 21,4 persen wilayah adat juga tumpang tindih dengan Hutan Produksi Terbatas. “(Ini) menempatkan wilayah adat yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi tersebut berada dalam ancaman eksploitasi sumber daya alam,” kata Cindy.
Asti Noor, Knowledge Management Officer WGII menyebut dalam temuannya, setidaknya terdapat 111 spesies mamalia di wilayah adat atau 14,4 persen dari total spesies mamalia di Indonesia. Dari data tersebut, 13 spesies berstatus Endangered, 9 spesies Critically Endangered, dan 12 spesies berstatus Vulnerable. Data tersebut merupakan hasil analisis sebaran perjumpaan spesies mamalia di Indonesia selama 20 tahun terakhir yang diperoleh dari platform Global Biodiversity Information Facility (GBIF) dengan data peta partisipatif wilayah adat.
“Sebagai pembanding, Indonesia merupakan rumah bagi 773 spesies mamalia atau 11,9 persen dari total spesies mamalia dunia,” ungkap Asti.
Data Key Biodiversity Areas dan keragaman mamalia di wilayah adat dapat menjadi data persandingan yang menunjukan kesinambungan peran masyarakat dan kontribusinya dalam mempertahankan keanekaragaman hayati. Sehingga, seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk meragukan efektivitas praktik konservasi berbasis masyarakat.
Asti menegaskan, data AKKM yang diagregasi oleh masyarakat sipil sangat memungkinkan untuk diadopsi dan diintegrasikan untuk mempercepat proses pengakuan hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dan dapat dihitung dan diakui dalam pelaporan pemerintah untuk capaian nasional dan global.


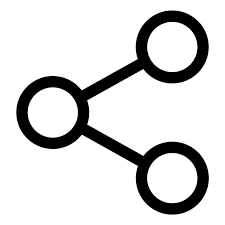 Share
Share
