
LIPUTAN KHUSUS:
Aliansi Masyarakat Sipil NTT Tolak Hasil COP30
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Alansi menilai komitmen COP30 hanya akan memperpanjang daftar janji global yang gagal menjawab luka lokal di NTT.
Iklim
Selasa, 25 November 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kekecewaannya atas hasil Konferensi Para Pihak (COP30) yang berlangsung di Belém, Brasil, pada 10–21 November 2025. Aliansi menilai perundingan yang berjalan dua pekan itu kembali mempertontonkan jauhnya komitmen global dari kebutuhan daerah rentan seperti NTT.
Aliansi ini terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT, Sahabat Alam NTT, Solidaritas Perempuan Flobamoratas (SPF), Mapala Universitas Citra Bangsa (UCB), Koalisi Kopi, dan Green Leadership Indonesia (GLI) wilayah NTT.
Dalam pernyataan sikapnya, yang dirilis pada Kamis (20/11/25), aliansi menilai pembahasan COP30 kembali didominasi isu teknis seperti baseline pasar karbon dan mekanisme carbon offset. Menurutnya, orientasi tersebut menunjukkan negosiasi iklim masih bertumpu pada instrumen ekonomi, sementara perlindungan ruang hidup masyarakat di daerah terdampak justru terpinggirkan.
“Tiga dekade COP belum membawa perubahan bermakna bagi wilayah rentan. Di NTT, tekanan akibat kekeringan, krisis pesisir, dan masuknya proyek industri terus meningkat tanpa perbaikan signifikan dalam tata kelola lingkungan,” kata Aliansi, dalam sebuah siaran pers, Minggu (23/12/2025).

Aliansi menyoroti pernyataan Pemerintah Indonesia di COP30 yang menyebut Indonesia berada “di jalur transisi energi yang kuat” dan tengah memperluas nilai ekonomi karbon. Pemerintah juga telah menargetkan transaksi karbon sebesar Rp16 triliun dengan potensi 90 juta ton CO2 dari sektor hutan, laut, energi, dan industri. Namun aliansi menilai orientasi tersebut mengarah pada akumulasi modal dan bukan perlindungan terhadap masyarakat rentan.
“Kami mempertanyakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung beban,” kata Aliansi.
Aliansi juga mengkritik daftar proyek pengurangan emisi yang ditawarkan melalui sertifikat domestik dan standar sukarela global. Mereka menilai skema itu belum menunjukkan jaminan keadilan bagi masyarakat lokal.
Pengkampanye Keadilan Ekologis Walhi NTT, Grace Gracelia, menyebut kesepakatan dalam COP 30 membawa dampak serius bagi wilayah rentan seperti NTT yang berada di kawasan kepulauan dan berhadapan langsung dengan perubahan iklim.
“NTT mengalami laju pemanasan yang lebih cepat, sementara ruang hidupnya terus tertekan oleh berbagai proyek ekstraktif,” ujar Grace.
Menurutnya, pendanaan iklim global yang dibahas di COP justru memicu perluasan proyek energi hijau dan energi baru terbarukan yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekologi.
Ia menilai beban ekologis NTT semakin berat akibat tumpukan proyek pariwisata, geothermal, dan perkebunan monokultur. Grace juga menyoroti pengabaian partisipasi bermakna masyarakat adat dan perempuan dalam sejumlah proyek geothermal di NTT.
“Pada akhirnya, mereka yang paling dekat dengan dampak justru paling jauh dari ruang pengambilan keputusan,” katanya.
Linda Tagie dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas menilai COP 30 gagal menjangkau persoalan substantif krisis iklim yang telah memicu pelanggaran HAM, kerusakan ekologi, hingga migrasi non-prosedural di NTT. Ia menyebut jargon “aksi iklim inklusif” yang dikampanyekan pemerintah tidak sesuai dengan praktik di lapangan.
Ia menilai, proyek energi baru terbarukan (EBT) di Poco Leok, Mataloko, Waesano, dan lokasi lainnya mempersempit ruang hidup perempuan dan memicu beban berlapis, termasuk kerja reproduksi yang semakin berat, risiko kesehatan, hingga kekerasan berbasis gender. Linda bilang ketidakhadiran analisis dampak gender dalam kebijakan iklim nasional memperdalam ketidakadilan yang ada.
“Pernyataan Linda itu menyoroti bahwa tanpa analisis gender, kebijakan iklim hanya akan mengulang pola ketidakadilan yang sama bahkan di tengah darurat krisis iklim yang kian mendesak,” ucap Linda.
Aliansi juga menyoroti penetapan Flores sebagai “Geothermal Island” sejak 2017 oleh Kementerian ESDM. Keputusan itu dinilai diambil tanpa keterlibatan publik dan tanpa kajian sosial-ekologis yang komprehensif. Transisi energi yang seharusnya menjadi langkah kolektif justru memunculkan konflik baru, terutama di lokasi proyek panas bumi seperti Wae Sano, Sokoria, dan Ulumbu. Riset Walhi-Celios (2024) mencatat potensi kerugian pendapatan petani mencapai Rp470 miliar dan kerugian output ekonomi hingga Rp1,09 triliun dalam dua tahun pertama.
Maria Ana Kristina Bara dari Mapala UCB menilai COP30 tidak lagi sejalan dengan mandat awalnya. COP kini lebih tampak sebagai arena transaksi berbasis karbon. Ia menyebut masyarakat di daerah rentan selalu menjadi pihak yang menanggung dampak, seperti warga Poco Leok yang berhadapan dengan proyek panas bumi, warga Sabu yang krisis air, hingga petani Kefamenanu yang gagal panen akibat cuaca ekstrem.
Sementara itu, Ainun Azizah Tasmira Salwa dari GLI NTT berpendapat bahwa generasi muda jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, meski telah lama menghadapi dampak krisis seperti kekeringan, persoalan sampah, dan tekanan pesisir tetapi tidak dilibatkan secara substansial dalam perumusan kebijakan.
Dalam deklarasinya, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai bentuk penegasan sikap dan penolakan mereka. Pertama, mereka menekankan bahwa komitmen iklim (NDC) Indonesia harus tegas dan terhubung dengan perlindungan ruang hidup di tingkat tapak, termasuk penghentian ekspansi industri fosil dan evaluasi proyek energi yang meminggirkan masyarakat.
Kedua, Pendanaan iklim global harus diarahkan ke wilayah rentan, termasuk adaptasi pesisir, pemulihan ekosistem, dan penguatan pangan lokal. Ketiga, Transisi energi harus melalui evaluasi konkret atas proyek berjalan dan bebas dari pelanggaran hak warga. Energi bersih NTT harus berbasis ekologi lokal.
Keempat, inklusivitas COP30 harus diterjemahkan ke kebijakan nasional dan daerah, dengan penerapan prinsip free, prior and informed consent (FPIC). Kelima, Perlindungan hutan tropis tidak boleh berubah menjadi komodifikasi karbon, tetapi harus melindungi hak masyarakat yang hidup di dalamnya.
Keenam, Adaptasi dan ketahanan iklim menjadi kebutuhan mendesak di NTT, terutama terkait kekeringan ekstrem, krisis air, dan ancaman pesisir. Aliansi juga mendesak agar pemerintah segera mencabut penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi.
Aliansi beranggapan keberhasilan COP30 tidak diukur dari dokumen diplomatik, tetapi dari perubahan nyata bagi masyarakat di garis depan krisis iklim. Kebijakan iklim, kata Aliansi, harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat. Mereka menilai komitmen COP30 hanya akan memperpanjang daftar janji global yang gagal menjawab luka lokal di NTT.


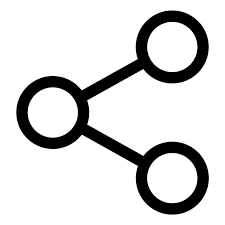 Share
Share

