Ambisi Bioenergi Kayu Butuh Lahan Setara 35 Kali Jakarta
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Hutan
Senin, 28 April 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Rencana pemerintah mengembangkan bioenergi kayu menuai tanggapan negatif dari kelompok masyarakat sipil. Sebab, pemanfaatan bioenergi kayu ini diperkirakan bakal mengakibatkan perampasan lahan, lantaran akan membutuhkan jutaan hektare lahan untuk pembangunan kebun kayu.
Dalam peta jalan terbaru, pembakaran kayu direncanakan mengambil porsi 12,2% dalam bauran energi terbarukan Indonesia per 2030. Padahal, bioenergi kayu tengah dipertanyakan sebagai sumber energi bersih karena polutif, tetap menghasilkan emisi besar, dan sangat rakus lahan.
Dalam laporan Trend Asia bertajuk “Ancaman Deforestasi Tanaman Energi”, ambisi bioenergi kayu pemerintah akan membutuhkan pasokan pelet kayu setidaknya sebesar 10,23 juta ton per tahun. Hal ini dapat berujung pada kebutuhan lahan seluas 2,33 juta hektare—setara 35 kali DKI Jakarta.
Kebutuhan lahan itu baru mencakup bauran listrik dari co-firing (pengoplosan pelet kayu bersama batu bara di PLTU), belum mencakup biodiesel dan bentuk bioenergi lain. Hal tersebut termasuk dalam niat pemerintah untuk menyiapkan 20 juta hektare lahan, termasuk 2 juta hektare yang tengah diterabas di Merauke, untuk cadangan ketahanan pangan dan energi. Secara total, bioenergi menjadi ancaman bagi meningkatnya deforestasi, yang dalam pantauan Forest Watch Indonesia (FWI), dalam periode 2021-2023 saja sudah menyentuh 1,9 juta hektare.

Dalam laporan “Hegemoni Politik Kebun Energi”, Koalisi Masyarakat Sipil menemukan bahwa dalam konteks Jawa, pengembangan perkebunan kayu didominasi oleh Perhutani dengan alas hukum pengelolaan hutan yang nyaris tak berubah dari praktik kolonial di bawah Jawatan Kehutanan Belanda (Boschwezen).
Bioenergi kayu disebut pemerintah akan meningkatkan ekonomi kerakyatan, karena ia melibatkan warga sebagai pemasok bahan bakar kayu. Namun dalam kajian pada 3 lokasi penanaman tanaman energi, Perhutani—yang menguasai 2,42 juta hektare atau 18% dari luas Pulau Jawa—mendominasi warga secara semena-mena dengan mengkategorikan “lahan kritis dan tidak produktif” dan menentukan jenis tanaman. Sementara masyarakat seringkali hanya dilibatkan sebagai buruh kontrak borongan.
“Proyek ini adalah perampasan ruang hidup yang terencana, dan akan menajamkan ketimpangan struktur penguasaan lahan dalam kawasan hutan,” ujar Rendi Oman Gara dari Sajogyo Institute, dalam sebuah keterangan tertulis, Kamis (24/4/2025).
Rendi mengatakan, proyek hutan tanaman energi justru merampas lahan garapan masyarakat dan mengkonsentrasikan tanah di tangan korporasi. Singkatnya, kebun energi akan turut menghambat reforma agraria dalam kawasan hutan.
Seperti terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Rendi bilang, penanaman gamal dan kaliandra sebagai komoditas biomassa di hutan Jawa telah melenyapkan kesempatan mendapatkan redistribusi lahan melalui reforma agraria. Perhutani mengembangkan kebun energi di atas tanah yang sejak pasca-reformasi diperjuangkan untuk diredistribusi.
Mas’ud dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), menuturkan, proyek bioenergi kayu ini berdiri di atas kebijakan di sektor kehutanan yang salah. Pada praktiknya, penetapan kawasan hutan umumnya tidak disertai dengan inventarisasi , identifikasi, dan penyelesaian hak-hak komunitas (adat dan/lokal).
“Sehingga wilayah adat dan lahan-lahan petani dikepung dan berada dalam klaim kawasan hutan negara,” kata Mas’ud.
Berdasarkan konsolidasi peta partisipatif di Jawa yang dilakukan oleh JKPP, lanjut Mas’ud, dari luas 90 ribu hektare ruang hidup masyarakat adat dan lokal, 62% atau 56 ribu hektare tumpang tindih dengan kawasan hutan. Hal ini menandakan bahwa keberadaan kebun kayu energi (hutan tanaman energi) di Jawa yang bekerja di atas kebijakan sektor kehutanan adalah salah satu bentuk pelegalan perampasan ruang hidup masyarakat.
Hal ini diperparah dengan berbagai praktik kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh institusi negara, termasuk militer dan kepolisian. Militer telah aktif terlibat dalam pengelolaan hutan sejak Orde Baru, namun penerbitan Peraturan Presiden No.5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan semakin memperbesar keterlibatan mereka.
Padahal kawasan hutan itu sendiri diklaim oleh negara tanpa adanya prinsip-prinsip keterbukaan sehingga penertiban kawasan hutan akan menjadi tuntas dan jelas apabila kawasan hutan itu sendiri tidak hanya legal namun juga harus punya legitimasi. Begitu pun proyek biomassa yang dibangun di atas kawasan hutan di Pulau Jawa.
“Sudah seharusnya data kawasan hutan dibuka, terutama yang berkaitan dengan Berita Acara Tata Batas, jika tidak ya kawasan hutan hanya klaim sepihak oleh negara tapi tidak pernah mendapatkan legitimasi dari masyarakat,” kata Anggi Prayoga dari Forest Watch Indonesia.
Menurut Anggi, apapun proyeknya, tidak akan berhasil jika pengakuan terhadap kawasan hutan tidak ada atau lemah. Ia mencontohkan proyek biomassa di Pulau Jawa yang marak ditanam sejak 2019 sampai 2025, tapi tidak pernah dipanen. Begitu pula proyek biomassa milik korporasi swasta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi juga mandek.
“Yang dipanen malah kayu dari hutan alam, bukan kayu rehabilitasi. Dan juga, untuk mentransformasi ketimpangan penguasaan lahan dalam kawasan hutan kita perlu mereformasi peran militer,” ucap Anggi.
Dosa militer, imbuh Anggi, sangat besar dalam eksploitasi sumber daya hutan dan deforestasi. Anggi bilang, militer menguasai bisnis-bisnis penting dalam kehutanan, legal maupun illegal, dan itu tidak pernah direformasi.
“Dosa mereka juga besar dalam menindas, memukuli, dan menekan perlawanan para korban-korban perampasan lahan dan industri ekstraktif di hutan,” katanya.
Kini, proyek bioenergi mendorong sistem kolonial tanam paksa modern ini di bawah alibi “transisi energi bersih” dan “perang melawan perubahan iklim”. Ironisnya, perkebunan skala besar dan deforestasi yang ditimbulkan dapat mendorong bencana ekologi yang langsung mendera situs penanaman, termasuk erosi tanah, banjir bandang, hilangnya biodiversitas, dan banyak masalah lain.
Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Bayu Maulana Putra, mengatakan alih-alih mendorong upaya untuk menekan naiknya emisi karbon dan mendorong ekonomi kerakyatan, sebagaimana klaim yang digulirkan oleh pemerintah, proyek energi biomassa justru berpotensi berjalan sebaliknya.
Bayu melanjutkan, proyek biomassa untuk memasok kebutuhan co-firing biomassa di PLTU, misalnya, berpotensi memicu deforestasi hutan alam sedikitnya 1 juta hektare, yang akan memperparah dampak bencana hidrometeorologi di Indonesia.
“Proyek biomassa juga akan menjadi peluang bagi korporasi kehutanan untuk memperlebar ceruk kekayaan yang secara bersamaan justru berpotensi memperlebar perampasan ruang hidup masyarakat,” kata Bayu.
Menurut Nadya Amelia Salsabila, dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), klaim pengurangan emisi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat kebun kayu energi pada implementasi transisi energi melalui skema co-firing biomassa ternyata berbalik arah.
“Alih-alih mendapatkan banyak keuntungan, justru merugikan secara sosial dan ekologis,” ucap Nadya.
Menyikapi persoalan yang sudah diuraikan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan sejumlah tuntutan. Yang pertama, penyegeraan redistribusi lahan kepada warga dalam kawasan hutan. Praktik sepihak klaim “lahan kritis dan tidak produktif” harus dihentikan, dan reforma agraria sejati harus disegerakan di kawasan hutan untuk menjaga hak masyarakat.
Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap transisi energi berbasis ekstraktivisme. Transisi energi tidak cukup hanya listrik “bersih” dan terbarukan. Ia tidak boleh bersifat eksploitatif dan melanggar hak masyarakat atas ruang.
Berikutnya, yang ketiga, pelaksanaan audit penetapan kawasan hutan. Klaim sepihak negara atas wilayah adat dalam prinsip domein verklaring harus dihentikan. Perlu ada audit untuk memetakan dan menegakkan hak tenurial masyarakat.
Selanjutnya, keempat, penghentian program co-firing biomassa di PLTU. Co-firing biomassa, sebagai salah satu bagian dari program bioenergi, adalah solusi palsu transisi energi yang tidak benar-benar netral karbon, bersifat eksploitatif, serta hanya memperpanjang usia PLTU. Ia tidak seharusnya masuk dalam rencana transisi energi Indonesia.
Terakhir, kelima, pencabutan militerisasi kawasan hutan. Keterlibatan TNI dan Polri sebagai “pengaman” kawasan hutan pada faktanya dijadikan alat pembungkaman, yang meningkatkan kekerasan dalam konflik agraria dan mendorong korupsi.
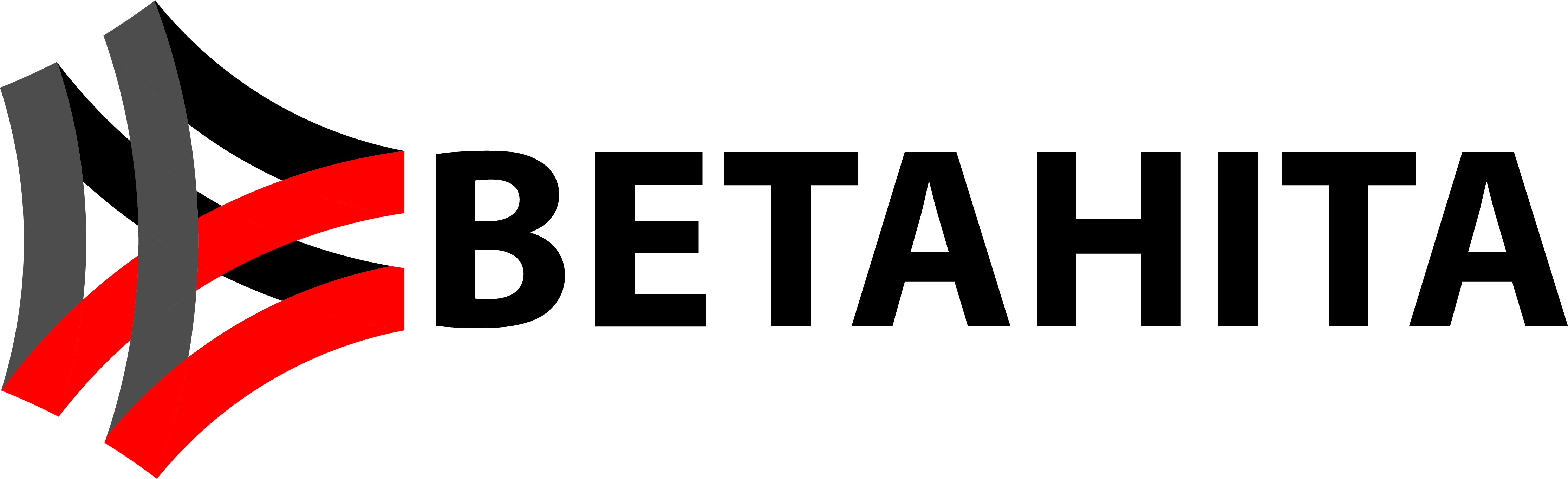


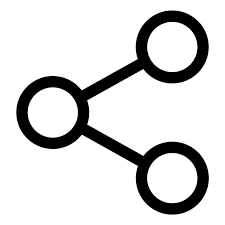 Share
Share

