Ekonomi sebagai Metabolisme
Penulis : Purwanto Setiadi, JURNALIS
OPINI
Selasa, 01 Juli 2025
Editor : Yosep Suprayogi
ADA satu aspek dari kegaduhan setelah pengeksposan penambangan nikel di pulau-pulau Raja Ampat yang luput diperhatikan, atau sengaja diabaikan. Aspek ini bertalian dengan fakta bahwa kerusakan akibat ekstraksi sumber daya alam sebetulnya membawa akibat buruk yang lebih jauh, sangat substansial, ketimbang sekadar kerusakan fisik yang kasatmata. Hal ini hanya bisa dipahami kalau orang sanggup mengimajinasikan ekonomi, yang mendorong kegiatan penambangan itu, sebagai metabolisme.
Kesanggupan untuk itu menemukan relevansinya dengan gagasan tentang ekosipasi yang dikemukakan Robertus Robet. Dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Filsafat Sosial Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta pada 12 Juni lalu Robet menyatakan perlunya peralihan dari emansipasi ke ekosipasi. Dengan ekosipasi, menurut dia, kecenderungan untuk kelewat individualis akibat emansipasi dapat dihindarkan dan pengakuan bahwa alam adalah subyek, bukan obyek yang terus-menerus dieksploitasi, dapat didorong.
Mereka yang mengikuti perkembangan pemikiran terkait dengan penghormatan dan pelindungan terhadap alam pasti dapat mengingat Christopher Stone. Pada 1972, melalui makalah berjudul “Should Trees Have Standing? -- Towards Legal Rights for Natural Objects”, dia mengajukan argumentasi bahwa pohon, sungai, laut, dan, tentu saja, alam memiliki hak hukum fundamental. Pendapat ini, kala itu, bisa terdengar konyol. Tapi seorang hakim di Mahkamah Agung menyitirnya dalam dissenting opinion-nya untuk satu kasus yang diputuskan pada tahun yang sama.
Berdasarkan semangat dari pendapat Stone pula beberapa negara kemudian menjalankan langkah progresif, melegalisasikan prinsip bahwa alam adalah landasan vital bagi kehidupan manusia, di antaranya Selandia Baru. Pada 2017, melalui kesepakatan di parlemen, negara ini mengakui Sungai Whanganui mempunyai hak, tugas, dan tanggung jawab sebagaimana badan hukum. Ia disebut sebagai “kesatuan hidup yang tak dapat dibagi-bagi…memadukan semua elemen fisik dan metafisikanya”.

Implikasi dari pengakuan formal semacam itu adalah kegiatan ekonomi tidak bisa lagi dilakukan semau-maunya. Imajinasi tentang ekonomi sebagai metabolisme jadi penting.
Sedikit penyegaran ingatan. Sebagai subyek dari bidang studi antardisiplin yang berlandaskan ilmu-ilmu biologi, kimia, fisika, dan lain-lain, metabolisme adalah reaksi kimia di dalam organisme hidup yang berlangsung melalui katalisis enzim. Reaksi ini meliputi produksi atau konsumsi energi (kalori) dan makromolekul (protein, lipida, asam nukleat), serta eliminasi sampah beracun.
Membayangkan ekonomi sebagai metabolisme, tentu saja, ia adalah metabolisme raksasa, walau, dalam model yang diintroduksikan Herman Daly, salah seorang perintis ekonomi ekologi, ekonomi “adalah cabang yang sepenuhnya milik lingkungan hidup, bukan sebaliknya”. Cabang, jelas, adalah bagian kecil belaka.
Inilah yang terjadi dalam ekonomi sebagai metabolisme: sumber daya alam diekstraksi (air, logam, mineral, biomassa, dsb.) dan sejumlah dampak dihasilkan (gas rumah kaca, logam berat, materi partikulat, sampah elektronik, dll.). Agar kelestarian bertahan atau keadaan berkelanjutan dapat dijaga, setiap tekanan terhadap lingkungan, baik di tingkat ekstraksi atau polusi, harus dipastikan tidak melampaui kapasitas daya dukung ekosistem di sekitarnya.
Dalam kenyataannya, jika melihat sejarah praktik ekonomi yang hingga kini berlaku hampir di mana saja, ekstraksi dan transformasi sumber daya alam menjadi barang yang dapat ditransaksikan sesungguhnya telah mendisrupsi siklus produksi dan reproduksi di alam. Dengan kata lain, metabolisme alam mendapat gangguan.
 Hamdi dan tiga Buruh panen sawit ditahan di Polres Mukomuko. Mereka dituduh mencuri sawit oleh PT DD
Hamdi dan tiga Buruh panen sawit ditahan di Polres Mukomuko. Mereka dituduh mencuri sawit oleh PT DD
Mungkin menyebut namanya bisa kontroversial di sini, tapi Karl Marx telah menyinggung hal ihwal ekonomi sebagai metabolisme dalam Das Kapital, karya besarnya, terutama berkaitan dengan kegiatan pertanian yang dijalankan secara kapitalistis serta antagonisme antara kota dan desa. Dia menggambarkannya sebagai siklus pertukaran esensial terkait dengan sumber daya dan energi antara manusia dan alam--meliputi proses-proses seperti perputaran nutrisi dalam tanah, siklus air, dan kesalingtergantungan antarorganisme hidup.
Ketika itu dia berpendapat bahwa “semua kemajuan dalam pertanian kapitalistis adalah kemajuan dalam seni, bukan saja merampok buruh, tapi juga merampok lahan”. Yang juga ikut kacau bersamaan dengan hal ini adalah interaksi metabolisme antara manusia dan bumi.
Sempat mendapat represi di banyak kawasan sepanjang abad ke-20, bersamaan dengan karya-karya Marx lainnya, konsep metabolisme itu kemudian dikembangkan oleh John Bellamy Foster; pada 1999 American Journal of Sociology menerbitkan artikelnya yang berjudul “Marx’s Theory of Metabolic Rift”. Interpretasi Bellamy berpengaruh luas. Belakangan dia diikuti antara lain oleh Kohei Sato, yang membahas metabolisme Marx dalam buku yang terbit pada 2020, Capital in the Anthropocene.
Poin tentang relasi antara manusia dan alam dalam konsep tersebut perlu mendapat penekanan. Ia lebih dari sekadar relasi seperti halnya orang-orang yang bertemu dan bekerja bersama-sama di satu kantor, umpamanya. Relasi ini sesungguhnya bertumpu pada keberadaan alam, yang dalam sejarah pembentukannya--berlangsung miliaran tahun--terdapat empat fase yang berbeda-beda tapi masing-masing menjadi dasar bagi kemunculan fase-fase setelahnya, yakni benda mati, vegetasi, makhluk hidup, manusia.
Dalam realitas yang dihasilkan dari proses tersebut memang terlihat bagaimana manusia baru muncul setelah semua hal, semua fase yang mendahuluinya, sudah mapan dan menyediakan tempat yang patut--seperti panggung yang telah rampung ditata demi penampilan seorang artis. Dan jelas pula bahwa seakan-akan manusia, dengan kelengkapan khas yang membedakannya dari makhluk hidup lain, bakal memanfaatkan kemampuan emosi dan intelektualnya serta perasaan dan kesadaran terhadap eksistensinya, dengan kesanggupan mengingat masa lalu dan belajar dari pengalaman itu demi membuat keputusan mengenai masa depannya, untuk bertindak benar; benar di sini adalah memegang teguh fakta bahwa tanpa sumber daya yang berasal dari tiga fase terdahulu manusia tak bakal bisa bertahan.
Tetapi yang sebetulnya juga harus diketahui, dan direnungkan, adalah mengapa fase-fase terdahulu menjadi keniscayaan bagi eksistensi manusia. Di sinilah perlunya pengetahuan tentang bagaimana tali-temali yang tak boleh absen di antara berbagai hal yang dihasilkan melalui fase-fase itu. Apa saja yang terdapat di alam tidak ada yang terisolasi. Pepohonan di hutan, misalnya, saling berkomunikasi, melalui jaringan jamur di bawah tanah; mereka berbagi nutrisi dan peringatan. Implikasinya adalah ketika hutan diratakan dengan tanah, yang musnah bukan hanya simpanan karbon, melainkan juga sistem komunikasi cerdas yang mungkin telah berusia ribuan tahun.
Penambangan, dalam konteks keributan terkait dengan apa yang terjadi di Raja Ampat, merupakan kegiatan ekonomi yang mengabaikan sama sekali kenyataan yang kompleks itu. Layaknya metabolisme, gangguan yang menyebabkan fungsi-fungsi alami bekerja tak normal atau bahkan berhenti sama sekali dapat membawa konsekuensi buruk bagi kesehatan, dan bahkan bisa fatal.
Pada awal 1970-an Nicholas Georgescu-Roegen sebenarnya telah mengingatkan perihal potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi, berdasarkan konsep entropi. Dalam fisika, entropi adalah pengukur ketidakteraturan dalam suatu sistem; entropi cenderung bertambah besar dari waktu ke waktu manakala sesuatu makin kacau. Menurut ekonom peletak landasan disiplin ekonomi lingkungan ini, semua kegiatan ekonomi harus dipahami sebagai sesuatu yang pada akhirnya mendegradasi lingkungan fisik, termasuk sumber daya alam; dan bahwa daya dukung bumi dipastikan bakal berkurang pada masa mendatang karena sumber dayanya yang terbatas, terutama mineral, terus diekstraksi dan dimanfaatkan.
Maka, kalau hal-hal tersebut dapat dimafhumi, pendapat yang menyederhanakan keberadaan sumber daya alam semata-mata sebagai “anugerah Tuhan bagi manusia” dan karenanya selalu harus dimanfaatkan, mestinya tidak muncul. Manusia, bagaimanapun, hanya punya peluang yang terbatas untuk memanfaatkan “anugerah” itu. Kate Raworth, ekonom yang mengintroduksikan konsep ekonomi donat, menggambarkan keterbatasan ini sebagai ruang di antara landasan kesejahteraan sosial dan batas daya dukung planet.
Menimbang kerusakan-kerusakan yang telah terjadi, dampak dari industri pertambangan atau kegiatan ekonomi ekstraktif yang lain, ada kata-kata Kenneth E. Boulding yang patut dicamkan; ia harus menjadi panduan menuju masa depan. “Siapa saja yang percaya bahwa pertumbuhan eksponensial dapat berlangsung selamanya di dunia yang terbatas,” kata ekonom yang tergolong awal dalam mengidentifikasi perlunya sistem ekonomi menyesuaikan diri dengan sistem ekologi yang sumber dayanya terbatas, “dia adalah orang gila atau seorang ekonom.”
 Dua pembudidaya rumput Laut mengangkut hasil panen di Desa Lobohede, Kecamatan Hawu Mehara, Sabu Ra
Dua pembudidaya rumput Laut mengangkut hasil panen di Desa Lobohede, Kecamatan Hawu Mehara, Sabu Ra
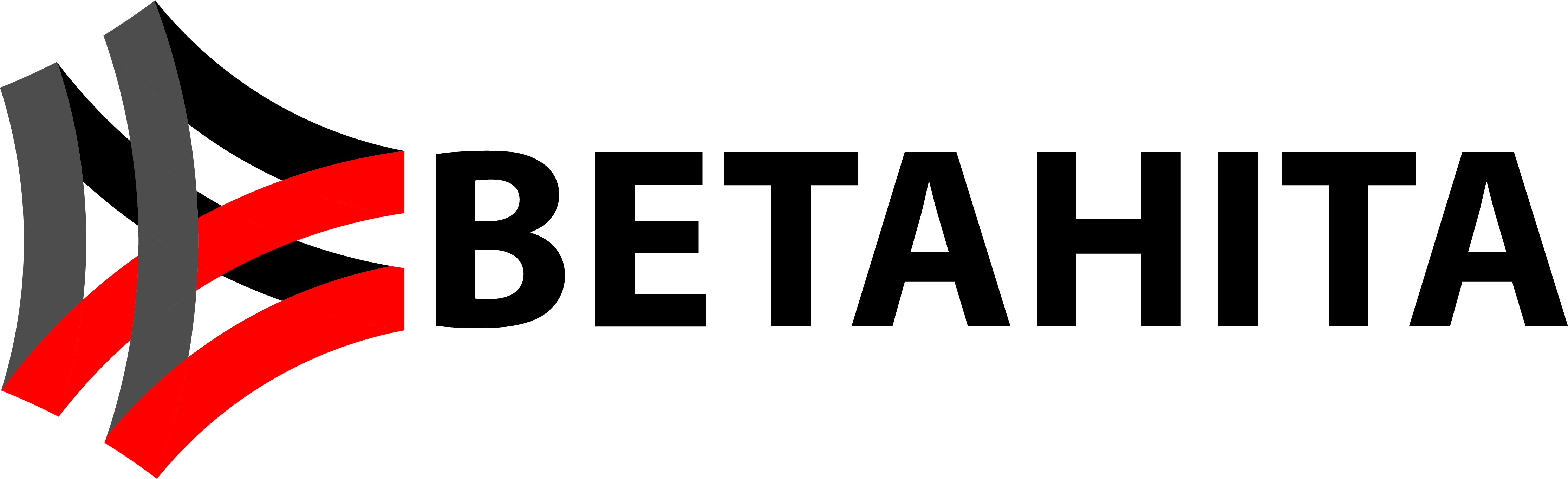


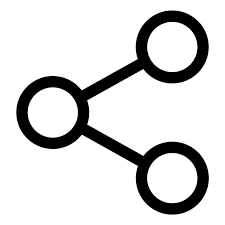 Share
Share

