Memanfaatkan, Bukan Mempercayai, Pasar
Penulis : Purwanto Setiadi, JURNALIS
OPINI
Selasa, 23 September 2025
Editor : Yosep Suprayogi
DALAM kuliah umum yang disampaikannya di Royal Economic Society pada akhir November 2007, Nicholas Stern menggambarkan perubahan iklim sebagai “kegagalan pasar terbesar yang pernah disaksikan dunia”. Mantan kepala ekonom Bank Dunia ini menggarisbawahi satu implikasi krusial: bahwa pasar, jika dibiarkan berjalan sendiri, tidak dapat diandalkan sebagai penggerak utama aksi iklim.
Meski begitu, dalam upaya mencapai transisi energi yang adil—yang cepat, demokratis, dan merata—mungkin juga perlu secara strategis memasukkan elemen-elemen logika pasar tertentu, seperti insentif, persaingan, dan inovasi. Tapi perangkat-perangkat ini harus tetap menjadi prioritas kedua setelah kepemimpinan politik dan transformasi sistemik.
Masalah yang timbul jika hanya mengandalkan pasar sudah luas diketahui. Polusi hanya dianggap sebagai eksternalitas, dan harga karbon—jika memang ada—terlalu rendah untuk mengubah perilaku dalam skala besar. Cakrawala dari motif cari untung adalah pendek, sementara tugas menjaga kestabilan planet ini menuntut komitmen jangka panjang. Iklim yang aman adalah barang publik, tapi pasar justru mendorong praktik “pembonceng gratis” (free rider). Ditambah lagi dengan kekuatan kepentingan bahan bakar fosil yang mengakar, infrastruktur bermasalah yang terkungkung, dan kesenjangan yang mendalam akibat alokasi sumber daya yang tak efisien, batasan-batasan tersebut menjadi jelas.
Kebutaan terhadap keadilanlah yang harus dihindari oleh transisi yang adil. Transisi ini lebih dari sekadar, misalnya, mengganti batu bara dengan panel surya; transisi ini tentang melindungi pekerja, mendukung masyarakat, dan memastikan kelompok rentan tidak tertinggal. Tanpa keadilan, peralihan ke energi bersih berisiko memperdalam ketimpangan dan memicu reaksi politik.

Tersebab oleh itulah pemerintah, gerakan sosial, dan perencanaan kolektif menjadi sangat penting. Merekalah yang menentukan arah, menetapkan aturan main, dan memastikan bahwa pasar melayani kepentingan publik, bukan sebaliknya. Hanya dengan demikian insentif, persaingan, dan inovasi dapat dimanfaatkan sebagai alat transformasi, alih-alih dibiarkan begitu saja, yang justru mereproduksi krisis yang sedang kita coba atasi.
Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana memanfaatkan logika pasar tanpa membiarkannya mengambil alih. Langkah pertama adalah membuat para pencemar membayar kerusakan yang mereka timbulkan (polluter pays principle), sambil tetap memastikan ada keadilan. Pajak karbon, misalnya, hanya akan berhasil jika dikombinasikan dengan langkah-langkah redistributif—seperti jaring pengaman sosial atau dividen langsung—yang melindungi rumah tangga biasa dari biaya yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, dana dan subsidi publik harus dialihkan secara tegas dari bahan bakar fosil ke energi bersih dan terbarukan.
Modal juga akan sangat penting. Pemerintah, dengan keterbatasan anggaran, dapat mengarahkan investasi swasta ke proyek energi terbarukan dan infrastruktur hijau, sementara lembaga publik membantu menanggung risiko dan membangun kepercayaan. Instrumen seperti obligasi hijau dan dana iklim dapat memobilisasi sumber daya dalam skala besar, tapi hanya jika didukung standar ketat yang mencegah praktik greenwashing dan memastikan dampak nyata.
Langkah selanjutnya adalah membuka persaingan dan menyalurkan inovasi ke tujuan-tujuan sosial, sekaligus mengaitkan insentif dengan keadilan. Persaingan yang sehat dapat menurunkan biaya panel surya, turbin angin, dan penyimpanan, sehingga energi bersih dapat diakses lebih banyak orang. Persaingan juga dapat mencegah praktik monopoli yang telah lama mendistorsi ekonomi bahan bakar fosil. Sementara itu, insentif seharusnya tak hanya menghargai efisiensi tapi juga memastikan demokratisasi—melalui kepemilikan komunitas, pelindungan tenaga kerja, dan pembagian keuntungan yang menjadi landasan transisi menuju keadilan.
Kehati-hatian tentu saja tetap menjadi hal yang utama; pasar, bagaimanapun juga, tidak dapat diperlakukan sebagai peluru ajaib. Jika tidak dikendalikan, finansialisasi dan greenwashing dapat menciptakan gelembung baru yang sama sekali tak mengurangi emisi. Ketergantungan yang berlebihan pada perdagangan karbon atau janji-janji perusahaan berisiko mereproduksi ketimpangan, alih-alih menguranginya. Itulah sebabnya batasan dan pelindungan yang jelas sangat penting: instrumen pasar harus selalu berada di bawah kendali demokratis, investasi publik, dan upaya untuk menegakkan keadilan.
Dengan demikian, kita tidak mengabaikan peringatan Stern. Pasar, jika dibiarkan begitu saja, tetap menjadi mesin penyebab kerusakan iklim, bukan solusinya. Yang penting adalah memastikan bahwa ketika kita menggunakan manfaatnya—insentif, persaingan, inovasi—manfaat itu tetap terkendali, didisiplinkan oleh kepemimpinan publik, dan diarahkan menuju keadilan. Hanya dengan demikian, logika pasar dapat memainkan peran pendukung dalam menyelenggarakan transisi yang cepat, adil, dan demokratis.
Transisi yang adil berarti mengutamakan manusia ketimbang profit, dan menjaga pasar tetap pada tempatnya.
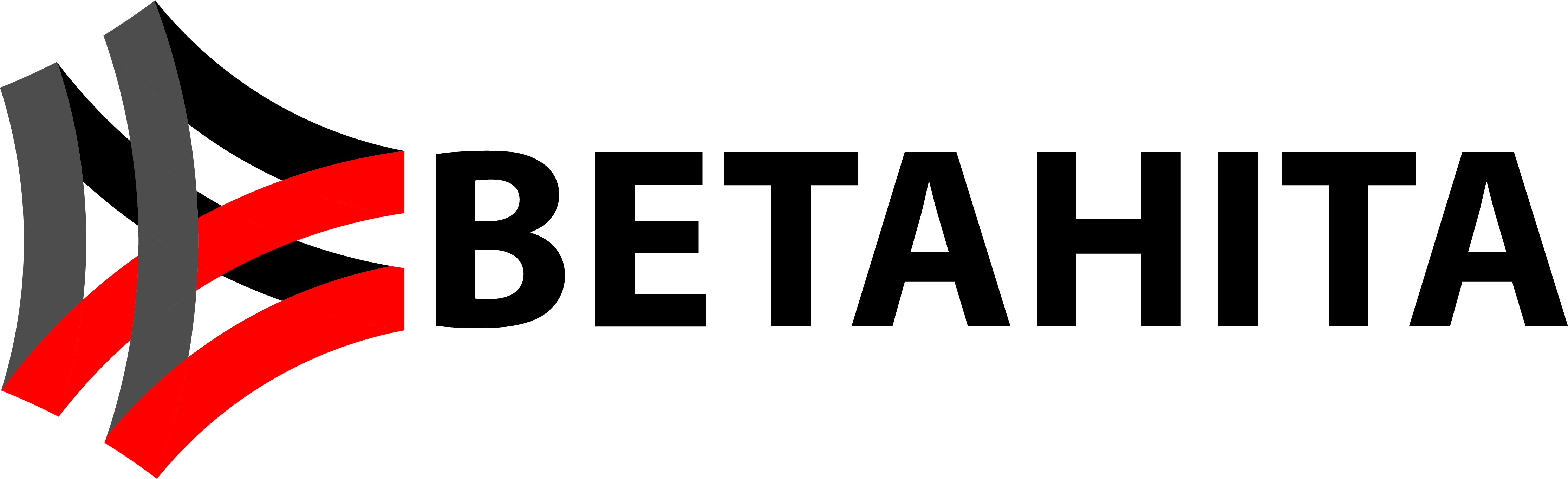


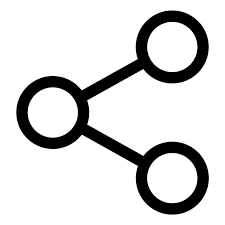 Share
Share

