Aliran Dana Bank Multilateral di Proyek Gas Papua
Penulis : Kennial Laia
Energi
Senin, 06 Oktober 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Pembangunan fasilitas produksi gas alam cair (LNG) baru di Teluk Bintuni, Papua Barat, dibiayai oleh sejumlah bank pembangunan multilateral yang memiliki komitmen iklim. Proyek tersebut juga menambah daftar panjang proyek ekstraktif berisiko tinggi di Papua, menurut sebuah riset terbaru.
Tiga bank tersebut–Asian Development Bank, International Finance Corporation, dan Asian Infrastructure Investment Bank–terlibat dalam pengembangan proyek LNG Tangguh sejak 2005, dengan pinjaman langsung sebesar USD750 juta, menurut temuan riset terbaru dari Recourse dan Trend Asia.
Pinjaman sebesar USD750 juta tersebut digelontorkan ADB pada 2005 dan 2016. Setelah itu IFC dan AIIB turut mendukung ekspansinya dengan menyalurkan dana melalui pemberi pinjaman perantara terhadap proyek yang sedang membangun fasilitas ke-empat (Train 4) tersebut.
“Ketiga bank pembangunan multilateral ini telah berkomitmen untuk menyelaraskan operasi dan investasinya dengan Perjanjian Paris, tapi mereka terus mendanai proyek gas fosil yang merusak iklim,” kata Juru Kampanye Keuangan Recourse, Marjorie Pamintuan.

“Kecuali jika mereka memperbaiki kebijakan energinya dengan menghentikan dukungan terhadap gas fosil, MDB (Multilateral Development Bank) akan terus gagal memenuhi komitmennya terhadap masa depan yang bersih dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sejak awal pembangunannya, proyek LNG Tangguh yang dioperasikan Britih Petroleum telah menggusur masyarakat adat dari kampung leluhurnya di Tanah Merah, merusak hutan mangrove terbesar di Asia Tenggara, hingga melepas jutaan ton emisi gas rumah kaca, menurut laporan tersebut. Luas hutan hutan di Papua Barat mencapai 24,5 juta hektare dan merupakan 78 persen dari wilayah Papua. Hutan ini menyerap sekitar 52 juta ton CO2e setiap tahunnya atau setara dengan total emisi yang dilepaskan Singapura. Sementara itu, luas hutan mangrove di Teluk Bintuni, wilayah proyek tersebut beroperasi, mencapai 2,25 juta hektare.
Hutan di Papua Barat berperan sebagai carbon sink yang paling efektif dan menjaga keseimbangan ekosistem. Hilangnya 136.000 hektare wilayah hutan Papua Barat diperkirakan berdampak pada pelepasan emisi CO2 sebesar 10,7 juta ton pada 2024.
Laporan tersebut mencatat emisi proyek LNG Tangguh diperkirakan mencapai 5 juta ton CO2e antara 2010–2015. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 8 juta ton CO2e setelah Train 3 beroperasi pada 2023. Total emisi tersebut empat kali lebih besar dari Timor Leste pada 2022.
Juru Kampanye Energi Trend Asia Novita Indri mengatakan, ekspansi dengan pembangunan fasilitas ke-empat (Train 4) LNG Tangguh, serta penambahan kapasitas gas dalam dokumen ketenagalistrikan (RUPTL) 2025 berpotensi menambah kerusakan lingkungan dan memperlebar ketimpangan di Teluk Bintuni.
Hal ini dikonfirmasi tim peneliti, ketika ADB mengonfirmasi adanya 11 hektare hutan mangrove yang dibabat untuk pembangunan fasilitas tersebut.
“Walaupun MDB telah berkomitmen untuk tidak membiayai proyek energi fosil, dukungan pendanaan ini membawa tanda tanya atas keseriusan komitmen iklim lembaga keuangan tersebut,” kata Novita.
Proyek gas jalan, masyarakat tetap miskin
Penambahan Train 3 untuk proyek yang dioperasikan British Petroleum Berau, anak perusahaan BP, disebut sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Data BPS Februari lalu menyebut pertumbuhan ekonomi Papua Barat mencapai 20,80 persen, tertinggi se-Indonesia pada 2024.
Novita mengatakan, angka tersebut tidak menggambarkan kondisi masyarakat di Teluk Bintuni. Dia menyoroti persentase penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 26,99 persen pada 2024. Persentase ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
“Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi belum mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengindikasikan manfaat belum dirasakan oleh masyarakat lokal, terlebih dalam mengentaskan ketimpangan struktural di Papua Barat,” kata Novita.
Laporan ini juga menekankan dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat adat yang dipindahkan ke Tanah Merah Baru dan Desa Onar Baru semakin mentereng sebab terjadinya pergeseran wilayah kelola pangan. Masyarakat yang mulanya melaut dan mengelola sagu kini harus bertani. Pergeseran pola konsumsi dari sagu ke gandum dan beras tercatat sebagai penyebab kasus kelaparan di Papua, seperti di Korowai dan Yahukimo.
Novita mengatakan, Indonesia berpotensi sulit untuk mencapai target Perjanjian Paris karena emisi metana yang dikeluarkan dari proyek gas lebih berbahaya dari karbon dioksida. Metana dapat memerangkap panas 80 kali lebih banyak daripada CO2 dalam jangka waktu 20 tahun lebih, dan emisinya tentunya mendorong percepatan krisis iklim.
“Bank-bank pembangunan multilateral harus berkomitmen untuk mengakhiri semua pendanaan untuk energi fosil, termasuk melalui lembaga perantara keuangan. Pada saat yang sama, para bank tersebut harus menghentikan narasi ‘gas sebagai energi transisi’ dan sebaliknya berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan publik guna mendukung percepatan transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan,” kata Novita.
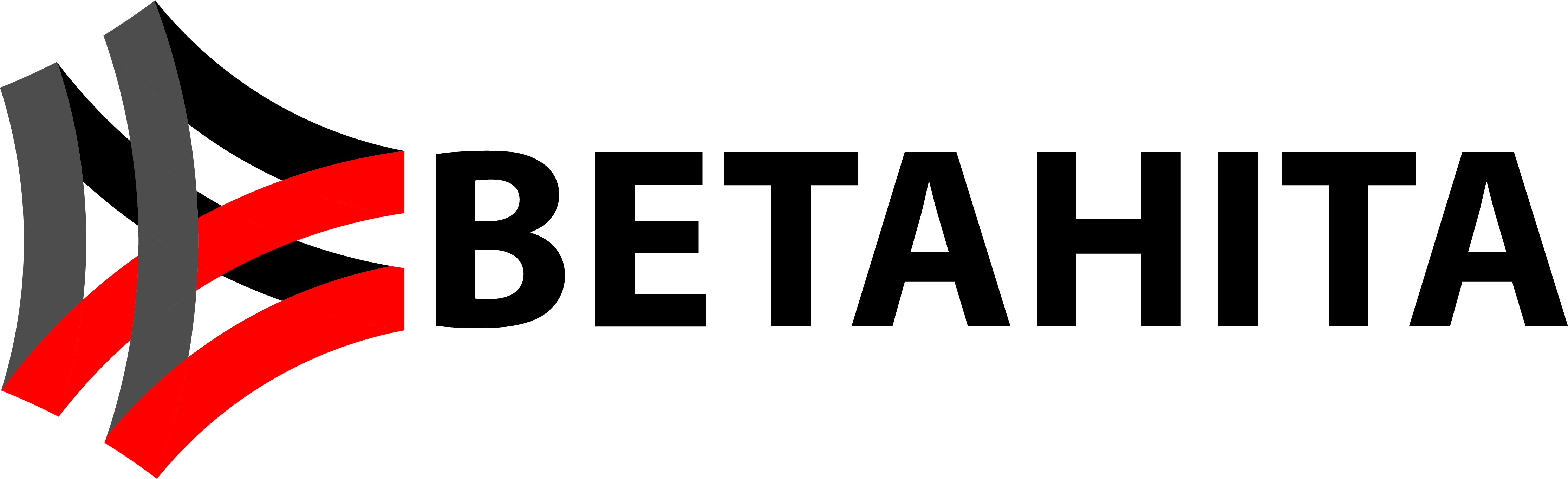


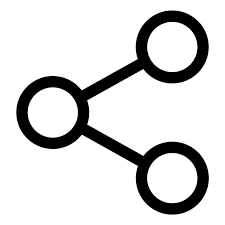 Share
Share
