Kegagalan Prosedural Pengaturan Anti-SLAPP Indonesia
Penulis : Sekar Banjaran Aji, GREENPEACE
OPINI
Senin, 17 November 2025
Editor : Yosep Suprayogi
HUKUMAN penjara lima bulan delapan hari dijatuhkan kepada 11 warga adat Maba Sangaji oleh Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Fakta lapangan menunjukkan, kriminalisasi ini terjadi karena warga desa menentang kegiatan penambangan nikel oleh PT Position, sebuah perusahaan yang telah merambah hutan adat, mencemari aliran sungai, dan merusak lahan pertanian warga desa. Metode protes mereka melibatkan ritual damai dan pemblokiran akses perusahaan secara simbolis. Namun mereka kemudian didakwa berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan (UU Minerba) atas tuduhan "menghalangi/mengganggu kegiatan pertambangan," dan dalam beberapa kasus lainnya, dakwaan seperti pemerasan (KUHP).
Sebelum kasus ini dimulai, banyak masalah muncul setelah PT Position menambang nikel di hutan adat Suku Maba Sangaji di Halmahera Timur, Maluku Utara. Hutan adat yang dulunya penuh kehidupan kini berubah menjadi lanskap kematian. Sungai Maba Utama dan anak-anak sungainya—Kaplo, Tutungan, Sabaino, dan Semlowos—semuanya rusak parah. Hutan di wilayah tersebut tampak tandus, dan sungainya telah tercemar oleh penambangan nikel, dengan luas konsesi sekitar 4.017 hektare.
Selama proses ritual adat dan pembacaan tuntutan adat, polisi dan warga telah berunding untuk meninggalkan senjata tajam: senjata warga ditinggalkan di tenda, dan begitu pula senjata polisi. Namun, polisi melarang pengibaran bendera adat karena dianggap dapat menghentikan kegiatan perusahaan. Menimbang hal-hal ini, tim pembela warga Maba Sangaji berargumen bahwa kasus ini jelas merupakan SLAPP dan warga harus dilindungi berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan dibebaskan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1/2023.
Proses penegakan hukum terhadap para aktivis lingkungan ini melibatkan berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran prosedural. Berdasarkan temuan lapangan yang kami himpun, penangkapan 27 warga terjadi saat mereka sedang melakukan ritual adat sebagai bentuk protes terhadap perusakan hutan oleh PT Position. Sebagian besar warga diangkut menggunakan kendaraan milik PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)—tindakan yang jelas menunjukkan kolusi antara polisi dan perusahaan tambang tersebut.

Di sini, polisi tidak hanya gagal bertindak independen tetapi juga secara efektif menjadi perpanjangan kepentingan perusahaan tambang tersebut. Selama proses interogasi, warga mengalami intimidasi, pemaksaan untuk menandatangani dokumen tanpa penasihat hukum, dan bahkan kekerasan fisik. Jadi keputusan pengadilan untuk menghukum warga, yang mengabaikan pembelaan Anti-SLAPP yang eksplisit berdasarkan UU PPLH dan PERMA 1/2023, mengungkap kelemahan fatal dalam sistem saat ini: perlindungan bersifat diskresioner oleh hakim, bukan prosedural dan wajib.
Keputusan tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang pada dasarnya tidak bermaksud membatasi individu yang berhak atas perlindungan hukum untuk memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti mereka yang telah mengajukan gugatan hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Warga melindungi hutan leluhur, sumber air, dan cara hidup tradisional mereka dari kerusakan lingkungan akibat penambangan nikel—sebuah contoh klise tentang memperjuangkan "lingkungan hidup yang baik dan sehat". Oleh karena itu, mereka menegaskan status mereka sebagai pembela.
Terdapat kekosongan prosedural yang memungkinkan kasus ini dikriminalisasi. Pertama, tidak adanya kewajiban untuk membatalkan gugatan lebih awal. Ketentuan Anti-SLAPP yang ada bukanlah aturan prosedural yang wajib, sehingga pihak pembela tidak dapat memaksa hakim untuk membatalkan tuntutan yang tidak jelas pada tahap awal. Akibatnya, warga yang bermaksud membela lingkungan terpaksa menjalani persidangan yang mahal dan mengintimidasi selama berbulan-bulan, padahal tujuan utama SLAPP telah terpenuhi. Kasus ini menjadi ironi dari putusan penting terbaru setelah Pengadilan Negeri Cibinong mengeluarkan putusan sela yang inovatif dalam perkara No. 212/Pdt.G/2025/PN Cbi. Pengadilan menolak gugatan terhadap ahli lingkungan Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis, dan secara resmi mengakuinya sebagai SLAPP. Ini menandai pertama kalinya pengadilan di Indonesia menerapkan prinsip Anti-SLAPP secara eksplisit pada putusan sela.
Kedua, UU Pertambangan sebagai senjata kriminalisasi. Putusan pengadilan yang menghukum warga Maba Sangaji secara efektif menolak penerapan Pasal 66, dan justru berfokus secara sempit pada pelanggaran teknis UU Pertambangan (Pasal 162 UU Minerba). Ketentuan UU Pertambangan tentang "penghalang" (Pasal 162) berfungsi sebagai instrumen Anti-SLAPP de facto yang ampuh bagi korporasi, serupa dengan bagaimana UU ITE digunakan di tempat lain. Interpretasi sempit ini memprioritaskan izin korporasi dan sanksi pidana khusus sektor ini di atas hak konstitusional dan hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik dan perlindungan lingkungan. Hal ini menciptakan lingkungan hukum di mana proses ekstraksi sumber daya dilindungi lebih ketat daripada hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.
Ketiga, perlunya integrasi prosedural untuk menghentikan kegagalan sistemik yaitu penggunaan instrumen hukum yang represif untuk menghalangi atau menghukum partisipasi publik. Perlindungan tersebut harus lebih luas dari UU PPLH dan dimasukkan ke dalam Peraturan Anti-SLAPP Umum atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang ini harus mengamanatkan aturan prosedural yang memungkinkan mosi khusus bagi hakim untuk segera menghentikan dan membatalkan setiap perkara yang dianggap sebagai SLAPP, terlepas dari sektornya (lingkungan hidup, antikorupsi, hak asasi manusia).
Kriminalisasi dan hukuman selanjutnya terhadap 11 warga Maba Sangaji, meskipun terdapat dokumentasi yang jelas tentang status mereka sebagai pembela lingkungan hidup adat, menunjukkan bahwa perlindungan Anti-SLAPP yang ada di Indonesia (Pasal 66 UU PPLH) secara substantif lemah, tidak ada secara prosedural, dan pada akhirnya tidak cukup untuk melindungi warga negara dari kekuatan korporasi yang memanfaatkan sistem peradilan. Hasil tragis dari kasus Maba Sangaji menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan reformasi hukum. Undang-undang Anti-SLAPP yang sektoral dan non-prosedural adalah harimau ompong yang gagal ketika diuji terhadap kepentingan korporasi yang kuat, terutama di wilayah yang kaya sumber daya. Hukuman atas warga Maba Sangaji berfungsi sebagai peringatan terakhir: Indonesia harus mengadopsi mekanisme Anti-SLAPP yang kuat, universal, dan didukung secara prosedural untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negaranya dilindungi dari pelecehan yudisial.
Sekar Banjaran Aji adalah seorang pengacara lingkungan dari Indonesia yang meyakini bahwa litigasi iklim sangat penting dalam melindungi masa depan umat manusia. Sekar kini bekerja sebagai Juru Kampanye Hutan untuk Greenpeace Indonesia dan menjabat sebagai Koordinator Jaringan Pengacara Kepentingan Publik (PIL-Net) Indonesia untuk periode 2023-2026. Pendapat ini tidak mencerminkan pandangan Organisasi saya.
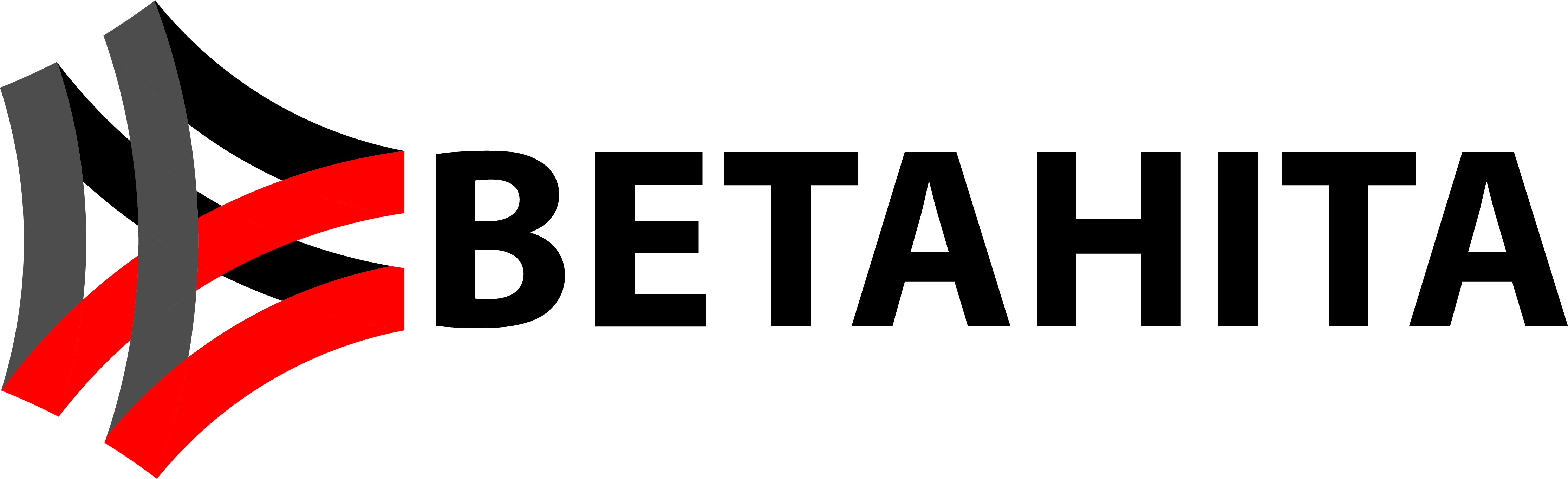


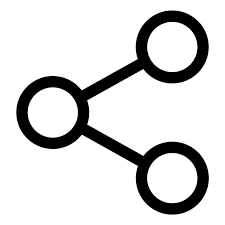 Share
Share
